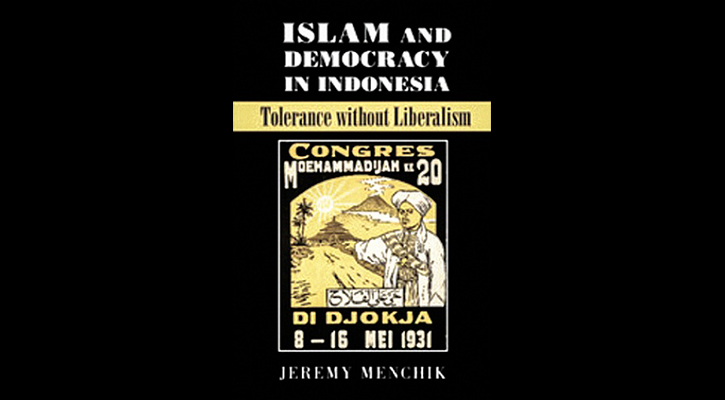
21 Mar Toleransi Tanpa Liberalisme
Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism
Penulis: Jeremy Menchik
Penerbit: New York: Cambridge University Press
Tahun Terbit: Januari 2016
Tebal: xv + 207 halaman
Mengapa kalangan muslim di Indonesia lebih toleran terhadap orang Kristen dibandingkan terhadap kelompok minoritas Islam? Menchik menyuguhkan temuan yang meyakinkan.
NAHDLATUL Ulama, sering disebut organisasi kemasyarakatan paling toleran di negeri ini, menjadi pilar bagi Islam yang ramah. Meyakini Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk Indonesia yang final, NU jadi tulang punggung “Islam Nusantara”: dekat dengan budaya lokal, nasionalis, tidak mengancam.
Begitu juga Muhammadiyah. Dalam berbagai peristiwa dialog antar-agama, ormas ini selalu jadi pionir. Bahkan Din Syamsudin, salah satu mantan pemimpin tertingginya, dikenal sebagai penggerak dialog antar-peradaban tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga global.
Jika klaim ini betul, mengapa keduanya seperti tak kuasa menahan aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah? Bahkan bukankah pelaku kekerasan anti-Ahmadiyah dan anti-Syiah baru-baru ini, di Cikeusik (2011) dan Sampang (2011 dan 2012), justru massa NU? Mengapa ada buku Kristen Muhammadiyah (KrisMuha, 2009), karya dua aktivis Muhammadiyah, tapi tak (akan) ada buku berjudul Ahmadiyah, Muhammadiyah (AhMuha)?
Jeremy Menchik masygul dengan puzzle seperti di atas, tapi kemudian menulis disertasinya tentangnya, yang jadi buku ini. Temuan-temuan Menchik -kini pengajar di Universitas Boston, Amerika Serikat- orisinal, meyakinkan, dan relevan. Meski aksi kekerasan di atas tak dibahas khusus di sini, buku ini sangat membantu kita dalam memahaminya.
Menchik berpedoman pada definisi toleransi yang umu dalam ilmu politik: “willingness to put up with those things one rejects or opposess” (halaman 3). Di situ ada makna kesediaan untuk menanggung (beban) keberadaan orang lain yang sebenarnya tidak kita sukai.
Tapi, berbeda dengan umumnya ilmuwan politik (yang meremehkan agama atau Eurosentris), Menchik ingin melihat bagaimana muslim Indonesia sendiri memahami toleransi. Maka dia detail memeriksa tiga organisasi besar Islam (NU, Muhammadiyah, dan Persis). Dia tak hanya membaca sumber-sumber primer terkait dengan ketiganya (termasuk catatan rapat), tapi juga melakukan survei dan wawancara dengan seribu elite mereka.
Sulit meringkas temuan Menchik di sini. Tapi, yang pokok, dia menemukan bahwa toleransi yang dikembangkan ketiga organisasi di atas toleransi tanpa liberalisme -atau “toleransi komunal” (Bab 6). Meski sama-sama toleran dalam pengertian ini, NU lebih toleran dibandingkan Muhammadiyah, dan Muhammadiyah lebih toleran ketimbang Persis.
Berbeda dengan toleransi liberal, toleransi komunal lebih mendahulukan iman dan pilihan kelompok. Untuk itu, kebebasan individual bisa dibatasi. Ini yang menjelaskan mengapa heterodoksi (misalnya ajaran Ahmadiyah) bisa dikalahkan ortodoksi (mayoritas).
Kedua, jenis toleransi ini hanya mungkin dijalankan di bawah sistem yang menghargai pluralisme hukum. Inilah yang memungkinkan satu komunitas agama menjalankan norma hukumnya sendiri, di luar sistem hukum nasional. Misalnya, orang tua muslim bisa meminta agar pelajaran agama anaknya diberikan oleh guru muslim, bukan Buddha.
Akhirnya, ketiga, toleransi komunal mensyaratkan pemisahan urusan agama dari urusan sosial, bukan urusan agama dari urusan negara. Inilah yang memungkinkan mengapa ajaran Islam tertentu (misalnya boleh mengucapkan “Selamat Natal” tapi tak boleh mengikuti ritualnya) bisa dijalankan.
Mengapa jenis toleransi ini yang berkembang? Semuanya bermula dari keputusan para aktor (pemimpin ormas) untuk mengambil pilihan-pilihan tertentu ketika ormas didirikan pada awal abad ke-20, yang dicirikan oleh naiknya Kristenisasi dan merebaknya kontroversi pemurnian Islam. Panjang kisahnya, tapi ringkasnya, para elite NU (di Jawa Timur), Muhammadiyah (Jawa Tengah), Persis (Jawa Barat) lebih memilih menoleransi Kristen (Katolik), dalam tingkat yang berbeda, seraya bersama-sama tidak menoleransi Ahmadiyah.
Sekali dibuat, kata Menchik, dalam paparannya yang kaya dan mungkin terbit untuk pertama kali dalam buku ini, pilihan-pilihan awal itu mengalami pelembagaan. Ia menjadi path dependence yang menentukan pilihan-pilihan lain berikutnya, hingga kini.
Di era perjuangan kemerdekaan, jenis toleransi tak liberal di atas terbukti produktif turut mendukung nasionalisme Indonesia. Kata Menchik, productive intolerance-lah yang melahirkan godly nationalism, dengan Pancasila di pusatnya. Produk lain adalah kementerian agama dan, belakangan, konsep dan lembaga seperti “agama resmi”.
Ada aksi inklusi sekaligus ekslusi disini. Ditopang paham toleransi komunal, para tokoh NU, Muhammadiyah, dan Persis, bersama yang lain dalam Majlis Islam A’la Indonesia (MIAI), belakangan Masjumi, bermufakat menolak kelompok seperti Ahmadiyah. Pilihan ini disepakati para founding father dari kelompok-kelompok lain.
Selanjutnya, path dependency berulang. Untuk keperluan politis tertentu, toleransi komunal dikibarkan Presiden Sukarno dengan menerbitkan Undang-undang Nomor I (1965) tentang penistaan agama. Dan pada 2010, permintaan peninjauan kembali atas undang-undang ini, yang diajukan antara lain oleh Abdurrahman wahid, mantan petinggi NU dan Presiden RI, ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang sama (halaman 155).
Apakah toleransi komunal bertentangan dengan demokrasi? Di sini Menchik, membawa data Indonesia untuk dibandingkan dengan data dari banyak negara lain, menunjukkan kontribusi lain buku ini ke dalam perdebatan dunia soal agama, demokrasi, dan toleransi. Faktanya, kata Menchik, menurut standar mapan, Indonesia pernah demokratis atau sebaliknya. Dan, dalam hubungan agama dan negara, Indonesia bukan sebuah demokrasi sekuler atau teokrasi Islam, melainkan campuran religius-sekuler yang menjadi promosi nilai-nilai tertentu, seperti ketuhanan, sebagai tujuan utama baik ormas maupun negara.
Jadi ingat Gus Dur tentang negara yang bukan “bukan-bukan? Mungkin dia benar, trapi bukankah kita sekarang memiliki cara ucap dan pemahaman lebih baik tentang apa yang kita bicarakan?
Menchik betul ketika menyatakan, di beberapa tempat, bahwa temuan-temuannya mungkin tidak mengenakkan untuk para pegiat kebebasan beragama. Dia juga benar ketika menegaskan bahwa paparan yang akurat tentang situasi yang tak ideal lebih baik daripada paparan bohong, dongeng, atau tentang bidadari yang belum tentu ada. Sebagai bagian dari pegiat di atas, saya sarankan baiklah kita telan pil pahit ini! Lalu kita bekerja berdasarkannya, semampu kita. Bukankah advokasi yang baik harus didasarkan atas mapping fakta secara jujur dan benar?
Temuan pokok Menchik mencerminkan debat antara kebebasan (toleransi individual) dan kerukunan (toleransi komunal) yang maraknya belakangan ini. Untungnya, dia juga memberi tawaran solusi untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, berkaca pada negara-negara lain. Misalnya dengan mengadopsi sistem registrasi yang bertingkat, seperti diterapkan di Australia atau India.
Tapi Menchik kurang menekankan pilihan lain: lebih kencang mengibarkan bendera liberalisme, yang lebih menghargai pilihan individual. Pertama, pilihan itu lebih cocok dengan masa depan rezim hak asasi manusia internasional, yang mustahil disepelekan. Kedua, dasar-dasarnya bukan tak ada di republik ini, seperti dalam pikiran Nurcholish Madjid atau Gusdur, yang juga anak-anak NU. Akhirnya, ketiga, seperti ditunjukkan data Menchik sendiri, tingkat pendidikan dan pergaulan adalah prediktator yang baik untuk toleransi, dan rekor Indonesia terus membaik dari segi ini.
Sumber: Majalah Tempo, 21-27 Maret 2016.

